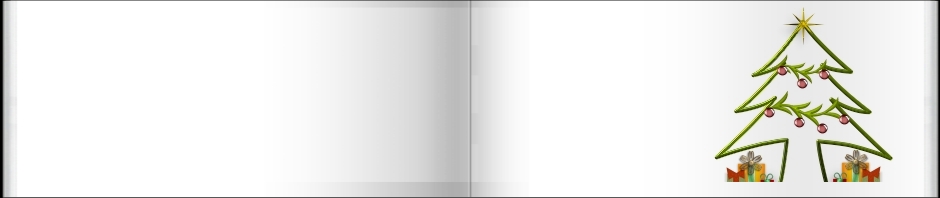HAM SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Pengantar
Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.
Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan
1
berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumberdaya alam)1 menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam)2 yang terkait dengan hak asasi manusia.
Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Semangat konstitusionalisme Indonesia harus mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan.
Meskipun demikian, pintu masuk melalui progresifitas teks konstitusi, tidaklah berarti pemahaman, tafsir dan implementasi penegakan hak-hak asasi manusia akan berjalan seiring dengan teks, karena hubungan teks dan konteks mengalami dinamika politik dan hukum. Kekuasaan yang tidak lagi mempedulikan dan peka terhadap persoalan rakyat miskins misalnya, akan sangat memungkinkan mereduksi jaminan kebebasan berekspresi dan berserikat. Atau juga penguasa yang merasa dirinya paling benar tanpa mau dikritik akan pula cenderung melahirkan penyingkiran hak-hak rakyat. Artinya, teks progresif belumlah mencukupi untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, karena ia membutuhkan tafsir progresif dan implementatif untuk merealisasikannya. Di konteks inilah, pergesekan antara tafsir kekuasaan dan kekuasaan tafsir akan sangat saling berpengaruh, utamanya dalam pemajuan hak asasi manusia (Wiratraman 2006).
1 Pendapat lain, menyebutkan lebih dari 5 pasal, yakni pasal 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, dan 34 (Hadjon 1987: 62).
2 Pendapat lain, menurut Asshidiqie (2006: 103-107), disebutkan ada 27 substansi atau materi hak asasi manusia.
2
Tulisan berikut akan mengurai dinamika teks-konteks yang mempengaruhi berjalannya pasal-pasal hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945. Pertanyaan kunci yang hendak dilihat adalah bagaimana pengaturan hak-hak asasi manusia secara konseptual dalam konstitusi, dan apakah paradigma negara dalam membuat kebijakan koheren dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang dirumuskan dalam konstitusi (constitutional rights), utamanya menyangkut paradigma negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia? Ataukah sebaliknya, inkoheren? Hal ini penting untuk merespon betapa kuatnya arus kapitalisme global yang menancap dalam berbagai kebijakan negara yang berpotensi menyingkirkan hak-hak konstitusional warga negara, utamanya paradigma liberal dalam jaminan hak asasi manusia. Bagian terakhir akan ditinjau bagaimana mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia.
Konsepsi HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen
Memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi moderen. Setidaknya, dari 120an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dideklarasikannya sejumlah hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights), yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia, maka secara bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata hubungan internasional.
Meskipun demikian, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1:
3
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Konsepsi HAM tersebut tidak hanya ditujukan untuk warga bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa di dunia! Di situlah letak progresifitas konsepsi hak asasi manusia di tengah berkecamuknya perang antara blok negara-negara imperial. Konsepsi yang demikian merupakan penanda corak konstitusionalisme Indonesia yang menjadi dasar tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (Wiratraman 2005a: 32-33).
DUHAM 1948 kemudian banyak diadopsi dalam Konstitusi RIS maupun UUD Sementara 1950, dimana konstitusi-konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang paling berhasil memasukkan hampir keseluruhan pasal-pasal hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM (Poerbopranoto 1953 : 92). Di tahun 1959, Soekarno melalui Dekrit Presiden telah mengembalikan konstitusi pada UUD 1945, dan seperti pada awalnya disusun, kembali lahir pengaturan yang terbatas dalam soal hak-hak asasi manusia. Dalam sisi inilah, demokrasi ala Soekarno (demokrasi terpimpin atau guided democracy) telah memperlihatkan adanya pintu masuk otoritarianisme, sehingga banyak kalangan yang menganggap demokrasi menjadi kurang sehat.
Di saat rezim Orde Baru di bawah Soeharto berkuasa, konsepsi jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 justru sama sekali tidak diimplementasikan. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dikebiri atas nama stabilisasi politik dan ekonomi, dan hal tersebut jelas nampak dalam sejumlah kasus seperti pemberangusan simpatisan PKI di tahun 1965-1967 (Cribb 1990; Budiarjo 1991), peristiwa Priok (Fatwa 1999), dan penahanan serta penculikan aktivis partai pasca kudatuli. Sementara penyingkiran hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terlihat menyolok dalam kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah, pengusiran warga Kedungombo (Elsam & LCHR 1995), dan pembunuhan 4 petani di waduk Nipah Sampang (Hardiyanto et. all (ed) 1995). Praktis, pelajaran berharga di masa itu, meskipun jaminan hak asasi manusia telah diatur jelas dalam konstitusi, tidak serta
4
merta di tengah rezim militer otoritarian akan mengimplementasikannya seiring dengan teks-teks konstitusional untuk melindungi hak-hak asasi manusia.
Setelah situasi tekanan politik ekonomi yang panjang selama lebih dari 30 tahun, desakan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia pasca Soeharto justru diakomodasi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut -- nyatanya -- cukup memberikan pengaruh pada konstruksi pasal-pasal dalam amandemen UUD 1945, terutama pada perubahan kedua (disahkan pada 18 Agustus 2000) yang memasukkan jauh lebih banyak dan lengkap pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Bandingkan saja kesamaan substansi antara UUD 1945 dengan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Untuk memudahkan memahami substansi, pemetaan berikut secara rinci mengemukakan pasal-pasal berbasis pada kualifikasi struktur konstitusi (Diatur dalam/luar Bab XIA) dan pemilahan substansi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Tabel:
Kualifikasi Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia
Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen
Bab XIA (Hak Asasi Manusia)
Di Luar Bab XIA
Pasal
Tentang
Pasal
Tentang
28A dan 28I ayat (1)
Hak untuk hidup
28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
28D ayat 1
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum
29 ayat (2)
Hak untuk beragama dan berkepercayaan
28D ayat (3)
Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
28D ayat (4) dan 28E ayat (1)
Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah
Hak Sipil dan Politik
28E ayat (1) dan 28I ayat
Kebebasan beragama 5
(1)
28E ayat (2) dan 28I ayat (1)
Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
28E ayat (3)
Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
28F
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
28G ayat (1)
Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
28G ayat (2) dan 28I ayat (1)
Bebas dari penyiksaan
28G ayat (2)
Hak memperoleh suaka politik
28I ayat (1)
Hak untuk tidak diperbudak
28I ayat (1)
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
28I ayat (1)
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
28I ayat (2)
Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif
28B ayat (1)
Hak untuk memiliki keturunan
18B ayat (2)
Pengakuan hukum dan hak adat tradisional
28B ayat (2)
Hak anak
27 ayat (2)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
28C ayat (1)
Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan
31
Hak atas pendidikan
28C ayat (2)
Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif
32 ayat (1)
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
28D ayat (2)
Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
33 ayat (3)
Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
28E ayat (1)
Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran
34 ayat (1)
Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
28E ayat (1)
Hak untuk memilih pekerjaan
34 ayat (2)
Hak atas jaminan sosial
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
28H ayat (1)
Hak hidup sejahtera
34 ayat (3)
Hak atas pelayanan 6
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
kesehatan
28H ayat (1)
Hak atas pelayanan kesehatan
28H ayat (2)
Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
28H ayat (3)
Hak atas jaminan sosial
28H ayat (4)
Perlindungan hak milik
28I ayat (3)
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
Dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang diperlihatkan di atas, maka terpetakan bahwa: (i) Pasal-pasalnya menyebar, tidak hanya di dalam Bab XIA tentang Hak Asasi Manusia. Sejumlah pasal tentang hak asasi manusia terlihat pula di luar Bab XIA (terdapat 8 substansi hak); (ii) UUD 1945 pasca amandemen telah mengadopsi jauh lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (iii) Banyak sekali ditemukan kesamaan substantif sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar Bab XIA, sehingga secara konseptual tumpang tindih, repetitif dan tidak ramping pengaturannya. Misalnya, hak untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam tiga pasal, yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29.
Meskipun dengan sejumlah kekurangan secara konseptual, pengaturan normatif pasal-pasal hak asasi manusia yang demikian sudah cukup maju, apalagi mengatur secara eksplisit tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (vide: pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen). Konsepsi tanggung jawab hak asasi manusia dalam UUD 1945 lebih menonjol kewajiban warga negara dibandingkan tanggung jawab utama negara, dalam hal ini pemerintah. Sebagaimana terlihat, kewajiban warga negara dalam soal hak asasi manusia diatur secara terpisah dan khusus (vide: pasal 28J), namun secara konseptual pengaturannya kurang tepat karena memasukkan konsep derogasi di dalam pasal 28J ayat (2), yang seharusnya
7
dalam konstitusi sebagai hukum (hak) dasar tidaklah perlu mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang umum atau mendasar sifatnya. Konsep derogasi haruslah spesifik, atau diterapkan dalam kondisi tertentu yang sifatnya darurat dan tidak semua hak bisa dibatasi atau dikurangi, karena ada sejumlah hak-hak yang sifatnya “non-derogable rights” (hak-hak yang tidak bisa sama sekali dibatasi atau dikurangi), seperti hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan.
Secara konseptual, perbaikan terhadap pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia adalah membongkar dan menata ulang berbasiskan pada substansi yang tegas penormaan dan rumusannya, dan menghapus pasal-pasal repetitif nan tumpang tindih. Saya kurang setuju dengan usul perangkaian pasal-pasal yang berbasiskan pada “generasi hak asasi manusia” sebagaimana dinyatakan oleh El Muntaj (2002: 115), karena generasi hak asasi manusia adalah ilusi semata, yang bilamana dipahami lebih jauh prinsip-prinsipnya, seperti prinsip indivisibilitas, interdependensi, dan inalienabilitas, maka tidaklah hak asasi manusia itu terpisah dan bergenerasi dalam sejarahnya.
Sedangkan menyangkut tanggung jawab hak asasi manusia, perubahan UUD 1945 perlu pula mengatur secara tegas dan progresif tanggung jawab utama negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Konsepsi progresifitas atau pemajuan hak-hak asasi manusia menjadi penting agar penyelenggara negara lebih memprioritaskan tanggung jawabnya, baik terhadap hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Pasal-pasal tentang tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia haruslah dibuat secara khusus, termasuk konsekuensi impeachment yang menjadi landasan konstitusionalnya (misalnya: memasukkan klausul ”terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia” dalam pasal 7A UUD 1945). Selain itu dengan kemungkinan momentum politik tertentu, perlu dipertimbangkan pula bila hendak melakukan perubahan total UUD 1945 (bukan bersifat amandemen), yakni menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia terlebih dahulu dalam pasal-pasal pembuka atau awal dalam struktur konstitusinya sebelum pengaturan tentang kekuasaan dan kelembagaan negara yang menjalankan kekuasaannya (Wiratraman 2007b: 9-10).
8
Paradigma Negara dalam Perlindungan HAM: Inkoheren?
Konstitusi, bagaimanapun, sebagaimana banyak ditafsirkan melalui materialisasi teks-teks telah memperlihatkannya sebagai konfigurasi politik yang bekerja. Artinya, konstitusi merupakan persepakatan secara sadar oleh para pembuat maupun pengambil kebijakan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki. Oleh sebab itu konstitusi, meski dipercaya dalam idenya memiliki nilai-nilai dan makna yang maha penting dalam menata kehidupan ketatanegaraan, sosial, ekonomi dan politik, ia tetaplah sebagai hasil dari pergesekan dan tarik-menarik representasi politik-ekonomi dominan yang memiliki kekuasaan tertentu dalam mempengaruhinya. Itupun belumlah menjamin konsistensi berlakunya dalam kebijakan-kebijakan negara.
Dengan perspektif demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa implementasi dari sebuah konstitusi yang baik belum tentu sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, utamanya menyangkut kebijakan-kebijakan suatu negara. Di Thailand misalnya, The People’s Constitution sebagaimana pernah dinyatakan oleh Lubis (2002: 157-158) sebagai konstitusi yang nyaris sempurna, tetapi nyatanya rezim politik Thaksin Sinawatra bisa dengan gampang mempermainkannya. Apalagi, ketika krisis politik melanda Kerajaan Thailand, militer atas restu Raja Bhumibol Adulyadej bisa pula menggulingkan Perdana Menteri dan mengganti konstitusi dengan konstitusi ala militer. Di Indonesia di masa Soeharto berkuasa juga menunjukkan hal yang serupa, konstitusi bisa dinegasikan oleh penguasa.
Kembali pada pertanyaan kunci yang diajukan dalam bagian Pengantar, apakah paradigma negara3 dalam membuat kebijakan koheren ataukah inkoheren dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang dirumuskan dalam konstitusi (constitutional rights),
3 Merriam-Webster’s 11th Collegiate Dictionary, paradigma diterjemahkan sebagai “an outstandingly clear or typical example or archetype”; “a philosophical and theoretical framework of a scientific school or discipline within which theories, laws, and generalizations and the experiments performed in support of them are formulated.” Secara lebih luas, disebut sebagai: “a philosophical or theoretical framework of any kind”.
9
utamanya menyangkut paradigma negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia?
Kita mungkin dengan mudah menyatakan bahwa paradigma pembangunanisme dan stabilisasi politik ekonomi dengan cara-cara kekerasan selama rezim Soeharto tidaklah mencerminkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Penculikan, intimidasi, penyiksaan, pembunuhan, pembantaian massal, adalah sederetan cara kekerasan yang dominan terjadi ketika rakyat menolak atau melawan kebijakan dan paradigma negara Orde Baru. Stigmatisasi “anti pembangunan” atau “antek PKI” demikian mudah meluncur dari mulut birokrat maupun politisi untuk menghajar rakyat, sehingga banyak sekali kekerasan secara sistematik, baik menggunakan peradilan maupun tanpa peradilan, seperti banyaknya penghilangan dan pembunuhan di luar proses peradilan (extra-judicial killings). Sakralisasi UUD 1945, peradilan beserta institusi hukum lainnya menjadi alat kekerasan, hukum diproduksi untuk pemenuhan kepentingan penguasa dan sekaligus menyingkirkan rakyat, kebebasan berekspresi ditekan dan sangat dibatasi. Kekerasan negara telah menjadi bagian dari paradigmanya.
Kini situasinya ‘berbalik’, lebih-lebih pasca amandemen UUD 1945. Desakralisasi UUD 1945 dengan empat kali amandemen, program reformasi peradilan didukung banyak pihak, termasuk secara politik dan didanai sejumlah lembaga donor asing, hukum-hukum represif telah banyak yang dicabut dan digantikan dengan sejumlah perundang-undangan yang lebih terbuka proses pembentukannya, kran kebebasan berekspresi kini relatif terbuka cukup lebar, dan (apalagi) ditopang oleh banyaknya pasal-pasal hak asasi manusia. Kekerasan negara seakan telah berkurang, meskipun sesungguhnya masih saja kerap terjadi, termasuk pelanggengan impunitas.4
Dalam konteks demikian, nampak jelas bahwa politik hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945 yang dibangun pemerintah inkonsisten dalam implementasinya.
4 Kekerasan negara telah terjadi dalam beberapa kasus, misalnya pasca amandemen UUD 1945, peristiwa penembakan polisi maupun tentara yang menewaskan sejumlah masyarakat adat dan petani dalam kasus Bulukumba (Sulawesi Selatan), kasus Manggarai (Nusa Tenggara Timur), dan kasus Alas Tlogo (Jawa Timur) ; kekerasan terhadap pekerja pers (Kasus Tomy Winata vs. Tempo, dll.); dan kasus pembunuhan aktivis pembela HAM Munir.
10
Meskipun demikian, perlu pula dipahami bahwa Negara telah mengubah animasi politik HAM-nya dengan memperkenalkan diskursus dominan hak asasi manusia yang dilekatkan dengan kepentingan liberalisasi pasar. Diskursus dominan tersebut menyulitkan publik untuk mengatakan inkonsisten dalam sejumlah kerangka implementatifnya, karena hukum beserta produk perundang-undangannya direproduksi justru untuk melegalisasikan kebijakan represif. Oleh sebabnya, tidak begitu mengherankan bila politik pembaruan hukum di Indonesia lebih diarahkan pada disain neo-liberal.
Mungkin Asshidiqie tidak 100% keliru dengan menyatakan bahwa dalam praktiknya penegakan HAM sangat dipengaruhi oleh corak praktik politik yang berlaku pada suatu negara. Jika politiknya demokratis, maka upaya penegakan HAM menjadi lebih prospektif. Begitu pula sebaliknya, jika politiknya otoritarian, maka alih-alih menegakkan HAM, yang justru biasanya terjadi adalah merebaknya praktik kejahatan HAM. Namun, dalam keadaan demokratis pun, jika para penegak hukum tidak memiliki kemauan kuat untuk menerapkan law enforcement dan justice enforcement, kejahatan HAM dapat saja tetap terjadi (Asshidiqie dalam El-Muntaj, 2005 : ix).
Namun dalam kerangka hukum disain neo-liberal, politik yang demokratis memanglah sangat diharapkan untuk menunjang pembaruan hukum, bukan bercorak politik otoritarian. Maka, secara paradigmatik, proses-proses untuk mendisiplinkan demokrasi diperlukan sebagai prasyarat untuk menginjeksikan program-program pembaruan hukum beserta kelembagaannya, seraya tetap ramah pada liberalisasi pasar. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, program-program pembaruan hukum dikemas dengan bingkai diskursus yang disahihkan melalui sirkuit kekuasaan dan legitimasi intelektual dalam bentuk good governance, access to justice, dan poverty reduction strategic programs. Oleh sebabnya, tidak terlampau terkejut karena dukungan pendanaan demikian deras mengalir tidak saja kepada pemerintah, melainkan pula bagi organisasi non-pemerintah, termasuk forum-forum multi-stakeholder yang menjadi “jembatan” komunikasi dan proyek bersama.
11
Pendisiplinan pembaruan dalam paradigma ini kongkritnya adalah ‘kerangka hukum untuk pembangunan’ (legal framework for development) yang didesakkan Bank Dunia, baik secara langsung maupun melalui ‘titipan’ ke lembaga donor dan multi-stakeholder lainnya, telah berhasil memistifikasi peran-peran strategis organisasi non-pemerintah melalui model ‘partisipasi-kemitraan’ dan menyebabkannya tidak lagi peka terhadap problem mendasar hak-hak asasi manusia (Wiratraman 2007a: 54-61).
Sederetan perundang-undangan yang merupakan prasyarat utang (baca: pesanan) proponen neo-liberal menjadi dominan terjadi pasca jatuhnya Soeharto di 1998, dan ini beriringan dengan reformasi hukum. Tiga gelombang undang-undang perburuhan sejak 1997 hingga 2006 telah nyata merepresi secara halus dan sistematik hak-hak buruh di Indonesia (softhening rights violations), melalui strategi tekanan upah buruh murah, meliberalkan persyaratan kerja bagi pekerja asing, outsourcing (perjanjian kerja waktu tertentu), kemudahan pengusaha untuk memecat dan merekrut buruh, liberalisasi aturan pesangon dan jaminan sosial, liberalisasi mekanisme penyelesaian perselisihan buruh-pengusaha, dan kebijakan kelenturan pasar buruh. Bagi buruh Indonesia yang kondisinya surplus dan rentan di-PHK, maka tekanan neo-liberal tersebut telah nyata bertentangan dengan hak-hak konstitusional, utamanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2). Begitu juga terhadap privatisasi dan komersialisasi sumberdaya alam melalui UU Sumberdaya Air dan UU Penanaman Modal Asing, kian melengkapi disain legalisasi pelanggaran hak-hak konstitusional atau hak asasi manusia (legalized violation of human rights).
Keberhasilan mistifikasi yang demikian lebih disebabkan kecanggihan teknologi kekuasan mereproduksi diskursus good governance, access to justice, dan poverty reduction strategic programs, yang dalam prakteknya justru memperlihatkan kekuatan dominan neo-liberal yang mensubversi hak-hak asasi manusia. Dalam konteks demikian, mistifikasi atas kekuatan yang tidak berimbang telah cukup menyilaukan publik antara mana yang disebut human rights movement dengan human rights market friendly.
12
Jaminan kerangka normatif melalui konstitusionalisasi hak-hak asasi manusia telah dikooptasi dengan paradigma hak asasi manusia ramah pasar, yang tidak lagi menyoal konsisten dan inkonsisten (secara hukum), melainkan nyata sekali inkoheren antara teks (kerangka normatif dan kebijakan), konteks dan dinamika teks-konteksnya.
Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia
Dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen jelas menunjukkan tanggung jawab negara dalam HAM. Sedangkan dalam pasal 28I ayat (5) menegaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rumusan kata ‘dalam’ pada pasal 28I ayat (5), “....dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur dengan suatu perundang-undangan khusus, melainkan ‘dalam’ segala perundang-undangan yang tidak sekalipun mengurangi substansi hak asasi manusia dalam konstitusi. Konsep yang demikian haruslah dipahami oleh Negara sebagai konsep pentahapan maju kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui strategi legislasi (progressive realization).
Sejak amandemen konstitusi, dalam konteks kebijakan dan legislasi, salah satu mekanisme tambahan selain gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Hadjon 1987) dan Mahkamah Agung5, yang bisa memberikan perlindungan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (pasal 24C ayat 1). Wewenang MK yang bisa menjadi benteng perlindungan ketika hak-hak konstitusional dilanggar, adalah sangat penting dalam kehidupan demokrasi yang menegaskan keseimbangan kekuasaan, dalam
5 Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 13
konteks ini antara kekuasaan legislasi dan kekuasaan yudisial. Pertarungan politik legislasi, pesanan paket perundangan tertentu, atau mungkin kelemahan sumberdaya manusia di parlemen dalam membentuk suatu produk hukum, yang kesemuanya setiap saat bisa terjadi, bisa ‘dikoreksi’ maupun ‘dibatalkan’ melalui gugatan ke MK. Meskipun demikian, perlindungan hak-hak konstitusional belum tentu benar-benar bisa dijamin melalui mekanisme tersebut, karena sangat bergantung dengan otoritas penafsiran mayoritas melalui putusan sembilan hakim.
Misalnya, Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004, judicial review UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mayoritas hakim MK berpendapat liberalisasi outsourcing bukanlah persoalan yang bertentangan hak asasi manusia atau hak konstitusional. Begitu juga Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 020/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mayoritas hakim MK berpendapat membatalkan keseluruhan isi undang-undang tersebut, tanpa melihat aspek dampak terhadap korban dan keluarga korban yang kian tidak jelas proses rehabilitasi dan kompensasinya, termasuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan hak asasi manusia. Putusan tersebut dirasakan memperkuat pelanggengan impunitas yang sudah pekat terjadi di Indonesia.6 Menurut catatan Elsam, setidaknya putusan MK tersebut berdampak pada: (i) Hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban: terbukanya kembali ruang pengingkaran tanggung jawab negara atas kekerasan masa lalu; (ii) Hilangnya roh pengungkapan kebenaran dan keberlangsungan praktek impunitas (Saptaningrum et. all. 2006).
Meskipun demikian, dalam sistem ketatanegaraan, eksistensi Mahkamah Konstitusi haruslah diperkuat sebagai lembaga yang bisa menyeimbangkan kekuasaan Negara, baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Beberapa Putusan MK juga perlu diapresiasi sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional, seperti salah satunya dalam Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003, judicial review UU No. 12 Tahun 2003
6 Impunitas terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia terjadi bukan saja karena komitmen politik pemerintah yang lemah dalam upaya mendukung penegakan HAM, tetapi juga mandulnya peran Pengadilan HAM yang justru menjadi mesin legal impunitas pelaku pelanggar HAM berat (Cohen 2003; Cumaraswamy 2003; Wiratraman 2005b).
14
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam putusan ini, mayoritas hakim MK mengabulkan gugatan pemohon dengan substansi pemulihan hak-hak kewarganegaraan (hak-hak sipil dan politik) para anggota/simpatisan PKI.
Dalam rangka membangun mekanisme yang melindungi secara lebih kuat hak-hak konstitusional warga negara, perlu diatur dalam konstitusi tentang hak gugat konstitusional (constitutional complaint), yang kewenangan untuk memutuskannya ada di tangan MK. UUD 1945 pasca amandemen belum memberikan jaminan constitutional complaint, padahal bagi warga negara yang hak-hak dasarnya dilanggar (constitutional injury) senantiasa berhadapan dengan mekanisme apa yang bisa digunakan. Misalnya, dalam kasus Ahmadiyah, bila mereka merasa kebebasan beragama sebagai kebebasan dasar yang dijamin konstitusi dilanggar, maka mereka bisa menggunakan mekanisme constitutional complaint melalui Mahkamah Konstitusi.
Belajar dari praktek ketatanegaraan di Jerman, constitutional complaint memiliki fungsi ganda: Pertama, fungsi suatu pemulihan di luar kebiasaan (extraordinary remedy), yang memberikan hak bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya; Kedua, fungsi untuk menegakkan tujuan hukum dasar, dan menjalankan penafsiran dan pembangunannya (Alexy 2002: 254). Yang perlu dipertimbangkan dalam mengusulkan mekanisme ini adalah hukum acara yang berlaku haruslah rinci dan jelas, agar tidak berbeturan dengan mekanisme hukum lainnya. Dalam pengalaman Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, hukum acara diatur secara khusus dan rinci, seperti salah satu pasalnya menegaskan: “Any person who claims that one of his basic rights or one of his rights under Articles 20 (4), 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law has been violated by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.” (Article 90 (1), Federal Constitutional Court Act/BVerfGG).7
7 Secara lebih detil, prosedur beracara dalam mengajukan constitutional complaints di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman bisa dilihat pada pasal 90-95 (Fifteenth Section Procedure in cases pursuant to Article 13 (8a) above), Federal Constitutional Court Act/Bundesverfassungsgerichts-Gesetz/BVerfGG, Published on 12 March 1951 (Federal Law Gazette I p. 243), as published on 11 August 1993 (Federal Law Gazette I p. 1473), as last amended by the Act of 16 July 1998 (Federal Law Gazette I p. 1823).
15
Penutup
Menguatnya hak asasi manusia secara tekstual konstitutif, tidak serta merta kerangka normatifnya akan memberikan jawaban tuntas atas kerangka implementatifnya. Justru sebaliknya sebagaimana diingatkan oleh Baxi (2002: viii) dalam The Future of Human Rights, “Jumlah rakyat yang kehilangan hak-hak juga meningkat justru ketika standar dan norma hak asasi manusia kian lengkap. Semakin banyak orang yang berdiri memberkati kerangka normatif hak asasi manusia melalui instrumen konstitusional dan internasional, semakin meluas dan menajam lahirnya penderitaan rakyat yang secara eksistensi tersingkirkan perwujudan dan penikmatan hak-hak asasi manusianya.”
Oleh sebabnya, bangunan politik hak asasi manusia menjadi penting untuk terus menerus dikoreksi, tidak saja secara konsepsional dan pengaturannya, tetapi tantangannya justru bagaimana Negara mampu dan berdaya untuk mengimplementasikannya di tengah kekuatan besar liberalisasi pasar, yang menyuguhkan animasi politik hak asasi manusia yang mistifikatif. Dalam situasi demikian, konstitusionalisme Indonesia perlu terus menerus didorong untuk secara berani dan tegas menjamin serta melindungi hak-hak asasi manusia yang telah memiliki landasan hukum tertinggi sebagai hak-hak konstitusional. Dengan begitu, pembatasan kekuasaan secara sewenang-wenang akan terkelola dengan seraya terus menerus menghidupkan semangat konstitusionalisme, yang sekarang ini terus menerus tergerus oleh konglomerasi diskursus dominan dalam bingkai ‘human rights market friendly paradigm’.
Pustaka
Alexy, Robert (2002) A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.
Asshidiqie, Jimly (2005) “Pengantar”, dalam Majda El-Muntaj (2005) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta : Kencana.
16
Asshidiqie, Jimly (2006) Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MKRI.
Baxi, Upendra (2002) The Future of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
Budiarjo, Carmel (1991) “Indonesia: Mass Extermination and The Consolidation of Authoritarian Power”, dalam Alexander George (ed.) Western State Terrorism. Cambridge: Polity Press.
Cohen, David (2003) Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta. Jakarta: International Center for Transitional Justice. <www.ictj.org/downloads/Intended_to_Fail--FINAL.pdf> (accessed 20 August 2005).
Cribb, Robert (1990) The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali. Melbourne: Center for Southeast Asian Studies, Monash University.
Cumaraswamy, Dato’ Param (2003) Report on the Mission to Indonesia, July 15–24, 2002: As the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers (E/CN.4/2003/65/Add.2, 13 January 2003).
Elsam & LCHR (1995) Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Elsam.
Fatwa, AM (1999) Dari Mimbar Penjara: Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan. Bandung: Mizan.
Hadjon, Philipus Mandiri (1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hardiyanto, Andik et. all (ed.) (1995) Insiden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma’e Tembak. Surabaya: LBH Surabaya & YLBHI.
Lubis, Todung Mulya (2002) “Jaminan Konstitusi atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan”, dalam Melanjutkan Dialog dalam Reformasi Konstitusi di Indonesia: Laporan Hasil Konferensi Oktober 2001. Jakarta: International IDEA.
Majda El-Muntaj (2005) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta : Kencana.
Poerbopranoto, Koentjoro (1953) Hak Asasi Manusia dan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta : JB. Wolters.
17
Saptaningrum, Indriaswaty D, et all (2006) Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Jakarta: ELSAM.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005a) “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)”, dalam Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari 2005.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005b) “Possibilities For Ending Of Impunity In The Case Of East Timor”, paper for Human Rights Protection Mechanism, OHRSD-Mahidol University, Bangkok.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2006) “Kekuasaan Tafsir dan Tafsir Kekuasaan dalam Hukum”, Forum Keadilan, 2006.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007a) Good Governance and Legal Reform in Indonesia. Bangkok: Office of Human Rights and Social Development, Mahidol University.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007b) “Politik Hukum Amandemen Kelima UUD 1945”, position paper pada Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara dengan tema: “Memperkuat Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Melalui Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia 1945”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PusKon) Universitas 45 Makassar dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Makassar 29 Juni-1 Juli 2007.
Putusan Pengadilan
Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, judicial review UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Putusan MK No. 020/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003, judicial review UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
18
* R. Herlambang Perdana Wiratraman
Menamatkan Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (1994-1998), dan kemudian menyelesaikan Master of Arts (MA) dalam bidang Human Rights Program, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, Bangkok (2005-2006). Menulis sejumlah buku dan artikel yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri, serta aktif mengembangkan gerakan dan pemikiran kritis tentang hukum dan hak asasi manusia melalui sejumlah lembaga organisasi rakyat dan non pemerintah. Kini, sehari-hari bekerja sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia
di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
19